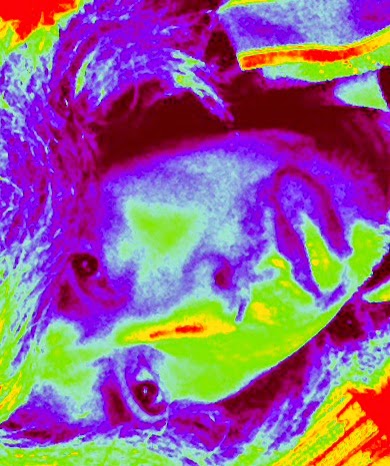Jika dicermati secara teliti, baik itu dari literasi atau pun berita media massa, maka bisa terdeteksi adanya semacam alur keterkaitan antara bisnis gelap narkotika dan senjata, yang diduga dikendalikan oleh aparatus intelijen global, dengan tujuan mencari dana tambahan bagi operasi tertutup maupun terbuka demi 'mengamankan bergulirnya globalisasi ke seluruh pelosok dunia'.
Ketika masih berlangsung perang dingin antara ideologi komunisme versus kapitalisme, para aparatus intelijen dunia Timur dan Barat memperoleh suplai dana yang melimpah tanpa pengawasan parlemen untuk saling bertarung, yang berujung dengan kemenangan kapitalisme Barat yang lantas berganti nama memproklamirkan diri menjadi ideologi globalisme atau lebih populer disebut globalisasi.
Semenjak globalisasi merebak, mendadak parlemen di banyak negara pengusung dan pengikut globalisasi mulai rewel dan risi melihat bujet aparatus intelijen global yang digelontorkan secara besar-besaran dan nyaris tanpa pengawasan. Akibatnya anggaran operasi intelijen mulai dikurangi sehingga aparatus intelijen global mulai melirik terjun mencari sumber-sumber dana ilegal dari bisnis gelap narkotika dan senjata; untuk membiayai operasi mereka di seluruh dunia tanpa perlu melapor dan tanpa pengawasan parlemen, karena anggarannya tidak diperoleh dari uang legal yang bersumber dari rakyat pembayar pajak.
Para pemimpin dunia bukannya tidak tahu hal ini -- terkecuali para pemimpin negeri ini yang saking polosnya rasanya kurang paham soal-soal seperti ini -- namun tak bisa berbuat banyak sehingga berlagak pilon: di atas tanah gembar-gembor memberantas bisnis haram narkotika dan senjata, namun di bawah tanah tutup mata mengamini maraknya bisnis gelap narkotika dan senjata demi perolehan tambahan anggaran guna membiayai kerja aparatus intelijennya mengamankan akselerasi globalisasi di muka bumi yang nyata-nyata butuh pasokan dana tak terbilang dibanding semasa perang dingin dulu.
Jika dalam uraian ini bisa terasa nilai obyektivitasnya, maka patut disimpulkan bahwa kobaran semangat pemerintah negeri ini untuk mengeksekusi tanpa henti dan tanpa pandang bulu keseluruhan terpidana mati narkotika, dengan alasan hendak meredusir persebaran narkotika dan demi menjungjung kedaulatan negara, justru terasa salah kaprah bak pungguk merindukan bulan!
Sebab, melihat anatomi bisnis haram narkotika dan senjata, maka membasminya pun hanya efektif jika diaktualisasi melalui rangkaian operasi kontraintelijen semesta dan kolektif yang melibatkan partisipasi semua aparatus keamanan negara berikut ragam warga masyarakat dari berbagai kelas sosial, anak-anak muda, aktivis LSM, aktivis mahasiswa, para guru dan dosen, seniman, sastrawan, pemusik, pekerja seni, awak media, pengurus osis, pemimpin informal, agamawan, kaum profesional, dan ibu-ibu rumahtangga; barulah terbuka harapan peredaran gelap narkotika dan saudara sekandungnya berupa penjualan senjata, bisa ditangkal hingga ke akar-akarnya.
Tanpa strategi membumi, amunisi yang diletupkan akan berbalik menjadi senjata makan tuan...
Salam psikologi ...
⬛⬛⬛}[Ψ]{COSACKOSAKclub}[Ψ]{⬛⬛⬛
⬜⬜ PsychopsycheStrategyCorps ⬜⬜⬜⬜⬜ Eksplorasi Sirkulasi ⬜⬜ Strategi➗Psikologi➗Fenomenologi | Think-tank Ψ Strategikal Psikologi
March 16, 2015
r e c o m m e n d a t i o n | Dinamika Bisnis Gelap Narkotika dan Senjata
r e c o m m e n d a t i o n | Menerima àtau menolak grasi manusia terpidana mati narkotika
Manusia, meminjam alam pikir kaum eksistensialis, bisa disebut sebagai mahluk yang tanpa jeda akan terus meng-ada, bereksistensi mengukuhkan makna keberadaan (jati) dirinya melalui relasi sirkuler saat ia mengambil inisiatif individual berinteraksi dengan lingkungan fisik maupun sosialnya dalam pola: stimulus-respon-stimulus.
Manusia, mengacu sudut pandang psikologi fenomenologi, diurai selaku mahluk inspiratif serba istimewa dalam balutan perpaduan daging & roh: daging yang me-roh dan roh yang men-daging. Perpaduan roh-daging ini mau tak mau mengkonstruksi manusia menjadi produk yang unik, sekaligus serba rumit dan lumayan sulit untuk dipahami tatanan ragam perilakunya: mahluk ciptaan Sang Penguasa Alam yang seutuhnya terbilang paling kompleks.
Derajat kompleksitas manusia, sampai kapan pun, diyakini oleh banyak akhli psikologi, tidak mungkin bisa disetarakan, digambarkan, atau disederhanakan dengan jejeran notasi angka-angka statistikal semata, karena berpotensi meredusir analisis diagnostikal psikodinamika sosok kepribadiannya secara utuh selaku: sebuah sistem psiko-fisik yang beraktualisasi menjalani survival kehidupannya melalui upaya penyesuaian diri secara terus menerus dengan lingkungannya. Dalam proses penyesuaian diri inilah manusia akan mengalami fase jatuh-bangun meniti gelombang arus kehidupannya dalam siklus integrasi-desintegrasi-reintegrasi.
Menyelami pisau analisis kaum psikoanalis, terkristal pandangan, apakah kelak manusia secara individual atau komunal berkemungkinan untuk menjadi orang baik dan buruk, ramah atau judes, pemaaf atau pendendam, malaikat atau psikopat, introvert atau ekstrovert, homoseks atau heteroseks, feminin atau maskulin, agresif atau pasif, pemarah atau penyabar, pemimpin atau pengikut, supel atau kaku; bahkan terperosok menjadi pemadat, pemasok, pengedar, ataupun bandar narkotika pada akhirnya: banyak bersandar pada proses formatisasi kepribadiannya sedari usia balita yang tidak selalu bisa berlangsung secara adekuat, otonom dan terkontrol. Sehingga dikatakan manusia itu sesungguhnya mahluk yang penuh dengan misteri yang sebahagian besar pola perilakunya justru dikendalikan oleh alam bawahsadarnya.
Dengan demikian, seiring dengan bergeloranya rencana eksekusi mati terpidana narkotika secara berjamaah, maka untuk menjawab hingar-bingarnya polemik perlu tidaknya grasi hukuman mati bagi para narapidana narkotika tersebut, tentunya bagi sang pemberi/penolak grasi terasa perlu kiranya mempertontonkan ke hadapan publik nasional maupun internasional perspektif kedalaman dan keluasan pemahaman holistiknya menyangkut "binatang apakah sesungguhnya manusia pebisnis haram narkotika, manusia terpidana mati narkotika maupun manusia korban narkotika itu".
Jangan sampai terjadi situasi, di mana para terpidana mati narkotika yang sudah ataupun akan dieksekusi di Nusakambangan, ternyata hanyalah para "cecunguk" di seberang lautan yang tak punya makna apa-apa dalam pemberantasan peredaran narkotika, sebab aktor utamanya justru ada di pelupuk mata namun tak terlihat sang pemberi/penolak grasi.
Kepada mereka yang lebih suka bekerja ketimbang membaca, gemar menambah koleksi burung istana namun lupa membeli buku-buku sastra, semoga bisa semakin berhati-hati, rajin berkontemplasi, demi terhindar dari predisposisi jebakan kesemerawutan perangkap eksistensi semu citra suci kedaulatan negara di balik tirai rencana gelombang rombongan eksekusi mati para terpidana narkotika.
Salam psikologi...
February 13, 2015
r e c o m m e n d a t i o n | Berpikir dahulu sebelum bekerja ...
Seperti ungkapan bijak kaum fenomenolog, bahwa 'ikan melihat segala hal kecuali air', maka orang nomor satu negeri ini, di hari akhir tahun 2014 ini, boleh jadi telah melihat segala hal problematika anak bangsa kecuali problematika perubahan perilaku dirinya yang teramat drastis semenjak ia bermukim di istana.
Tutur katanya pun tak lagi humoris penuh vitalitas seperti dulu; yang terasa sekarang jika ia menjawab pertanyaan ataupun kritikan, adalah gumaman kata-kata bernuansa robotik, mengalir mekanistik seperti kaset yang berulang diputar yang acapkali memperlihatkan inkonsistensi ekspresi antara jalinan kata dengan raut muka.
Jadi mengapa harus serba terburu-buru membangun Indonesia?
Mari berpikir, berpikir, dan berpikir terlebih dahulu sebelum bekerja, bekerja, dan bekerja.
Salam psikologi ...
November 26, 2014
r e c o m m e n d a t i o n | Menyimak tatkala rekrutmen posisi VIP para calon menteri Presiden Jokowi
(:-:) Barangkali, hari-hari ini, kaum oposisi yang kini bermukim di parlemen, tengah tertawa-tawa tergelak, terbahak, terpingkal, melihat begitu banyak kecerobohan dibuat saat dilaksanakannya proses rekrutmen para calon menteri, yang terkesan tanpa pedoman, tanpa konsep, tanpa strategi, dan tanpa didukung perspektif keilmuan: alias amburadul. Maaf!
Bayangkan, bagaimana mungkin diterima akal sehat, tatkala muncul inisiatif istana untuk menskaning kejujuran finansial para calon menteri dengan meminta pendapat KPK, yang muncul justru sodoran laporan tertulis formal dari KPK yang meyakini sekaligus berisi labelisasi perilaku koruptif individu-individu tertentu calon menteri dalam rona warna merah (paling lama satu tahun bakal diciduk KPK) dan kuning (paling lama dua tahun bakal diciduk KPK); tanpa sedikit pun mempertimbangkan azas praduga tak bersalah yang lazim dikedepankan sebelum lahirnya suatu keputusan hukum yang tetap, final, dan mengikat terhadap dugaan telah melakukan kejahatan koruptif sebagaimana yang disangkakan terhadap beberapa individu calon menteri tersebut. Belum lagi laporan tertulis formal seperti itu mudah sekali bocor akibat keteledoran atau dibocorkan atas dasar kesengajaan. Kita jadi was-was dan kembali teringat ke era orde baru yang dikenang bisa dengan gampang melabelkan seseorang sebagai "merah", atau subversif, atau non-Pancasilais, tanpa melalui proses peradilan.
Maaf!
Dalam proses rekrutmen di level posisi VIP, di belahan dunia mana pun lazimnya dilakukan secara senyap, bersih dari berkas, di mana evaluasi akan integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas, dijaring melalui pembicaraan antarpribadi antara pihak yang membutuhkan informasi dengan pihak yang dianggap kredibel memasok informasi yang dibutuhkan tersebut. Wajar jika istana membutuhkan informasi dari KPK dan wajar jika lantas KPK memasok informasi untuk istana, tetapi tidak dengan cara surat menyurat formal yang rawan sadap dan bocor, apalagi menabrak rambu rasa keadilan azas praduga tak bersalah, karena informasi yang diminta belum sah secara hukum, namun punya nilai strategis bagi istana. Akan terasa elegan jika proses penyampaian informasi cukup dilakukan lewat obrolan antarpribadi antara pihak istana dan KPK, mungkin sambil minum kopi di pagi hari. Maaf!
Amburadul dan hingar-bingarnya manajerial kantor transisi selaku tempat bercokolnya para pemikir istana yang nampaknya telah terperosok berkutat ke ranah administratif ketimbang strategik di bulan-bulan lalu, ditambah lagi berlanjut dengan kegaduhan nonproduktif dalam proses seleksi calon menteri selama seminggu ini, semoga tidak berdampak negatif, yakni menghadirkan keragu-raguan akan keterampilan manajerial maupun strategikal pihak istana itu sendiri.
Sekali lagi, maaf!
Sekali lagi, maaf!
Salam psikologi...
October 3, 2014
r e c o m m e n d a t i o n | Tritunggal presidensial Indonesia
(:-:) Sudah semakin nyata, Indonesia, dalam kurun waktu lima tahun mendatang, secara eksistensial akan dipimpin oleh 3 orang figur presiden, berpola tritunggal presidensial di mana: figurJokowi akan berkiprah selaku presiden formal di ranah pemerintahan, figur SBY akan terus berproses menjadi presiden informal penyeimbang dinamika perpolitikan, dan figur Prabowo yang nampaknya akan semakin lancar bergulir menata orkestrasi selaku presiden oposisional parlemen.
Masing-masing "presiden" ini saling memiliki "kelebihan" atau pun "kekurangan". Jokowi punya jangkauan infrastruktur, aparat, juga dana birokrasi yang gampang dimobilisasi, SBY punya banyak kawan serta paling paham sistem dan tarik-ulur geliat perpolitikan nusantara, sedangkan Prabowo punya potensi menstrukturi esensi maupun corak perundang-undangan yang hendak dilahirkan, dibekukan, diganti ataupun diperbaharui.
Kalau sejenak menengok ke belakang, model tritunggal presidensial pernah juga terjalin semasa rezim ode baru berkuasa, di mana Soeharto walau oleh rakyat kebanyakan dimitoskan sebagai penguasa tunggal, namun dalam persepsi kalangan elit ia terlihat berbagi kue kekuasaan dengan 2 figur lain: Widjojo Nitisastro selaku presiden teknokrat yang memegang kartu kepercayaan dunia Barat, dan Soedono Salim selaku presiden pebisnis yang memegang kepercayaan para pemilik modal dalam dan luar negeri, sedangkan Soeharto sendiri dipercaya sepenuhnya oleh TNI (ABRI). Mungkin Soeharto cerdas belajar dari kegagalan manajerial negeri seluas Indonesia oleh dwitunggal Soekarno-Hatta sehingga ia rela berbagi kekuasaan secara informal-eksistensial melalui langkah strategis merajut praksis tritunggal presidensial Soeharto-Widjojo-Soedono. Sayangnya kekompakan kerja sama tritunggal presidensial yang terbina membangun bangsa semasa orba, lambat laun di belakang hari tak lagi serasi dan mulai berjalan timpang kemudian retak tanpa ikatan, akibat ada kehendak Soeharto agak setengah memaksa untuk memasukkan Habibie pendatang baru dari Jerman yang ahistoris menjadi bagian tritunggal figur presidensial saat itu; yang nampaknya tidak diamini oleh dua figur lainnya. Akibatnya, harga yang harus dibayar menjadi teramat mahal, karena tanpa nyana saat krisis moneter menerjang negeri ini, Soeharto praktis harus menghadapinya sendirian, maka ia pun tumbang.
Hari ini kita belum bisa cepat tau, apakah tritunggal presidensial Jokowi-SBY-Prabowo, yang kebetulan terbentuk alami tanpa upaya rekayasa apa pun usai pilpres yang berlangsung meriah, akan menghadirkan berkah atau sumpah serapah, karena makna gestaltnya bergantung sepenuhnya pada keluwesan, kematangan, kedewasaan, dan kecerdasan intelektual maupun emosional di antara masing-masing figur terkait.
Walaupun orang Perancis bilang, sejarah senantiasa terulang!
Salam psikologi...
Masing-masing "presiden" ini saling memiliki "kelebihan" atau pun "kekurangan". Jokowi punya jangkauan infrastruktur, aparat, juga dana birokrasi yang gampang dimobilisasi, SBY punya banyak kawan serta paling paham sistem dan tarik-ulur geliat perpolitikan nusantara, sedangkan Prabowo punya potensi menstrukturi esensi maupun corak perundang-undangan yang hendak dilahirkan, dibekukan, diganti ataupun diperbaharui.
Kalau sejenak menengok ke belakang, model tritunggal presidensial pernah juga terjalin semasa rezim ode baru berkuasa, di mana Soeharto walau oleh rakyat kebanyakan dimitoskan sebagai penguasa tunggal, namun dalam persepsi kalangan elit ia terlihat berbagi kue kekuasaan dengan 2 figur lain: Widjojo Nitisastro selaku presiden teknokrat yang memegang kartu kepercayaan dunia Barat, dan Soedono Salim selaku presiden pebisnis yang memegang kepercayaan para pemilik modal dalam dan luar negeri, sedangkan Soeharto sendiri dipercaya sepenuhnya oleh TNI (ABRI). Mungkin Soeharto cerdas belajar dari kegagalan manajerial negeri seluas Indonesia oleh dwitunggal Soekarno-Hatta sehingga ia rela berbagi kekuasaan secara informal-eksistensial melalui langkah strategis merajut praksis tritunggal presidensial Soeharto-Widjojo-Soedono. Sayangnya kekompakan kerja sama tritunggal presidensial yang terbina membangun bangsa semasa orba, lambat laun di belakang hari tak lagi serasi dan mulai berjalan timpang kemudian retak tanpa ikatan, akibat ada kehendak Soeharto agak setengah memaksa untuk memasukkan Habibie pendatang baru dari Jerman yang ahistoris menjadi bagian tritunggal figur presidensial saat itu; yang nampaknya tidak diamini oleh dua figur lainnya. Akibatnya, harga yang harus dibayar menjadi teramat mahal, karena tanpa nyana saat krisis moneter menerjang negeri ini, Soeharto praktis harus menghadapinya sendirian, maka ia pun tumbang.
Hari ini kita belum bisa cepat tau, apakah tritunggal presidensial Jokowi-SBY-Prabowo, yang kebetulan terbentuk alami tanpa upaya rekayasa apa pun usai pilpres yang berlangsung meriah, akan menghadirkan berkah atau sumpah serapah, karena makna gestaltnya bergantung sepenuhnya pada keluwesan, kematangan, kedewasaan, dan kecerdasan intelektual maupun emosional di antara masing-masing figur terkait.
Walaupun orang Perancis bilang, sejarah senantiasa terulang!
Salam psikologi...
Subscribe to:
Comments (Atom)